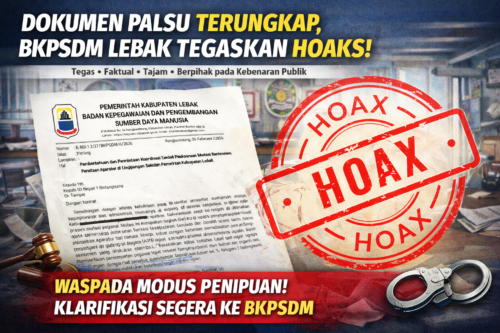Tokoh nasional Abah Elang Mangkubumi berpose di depan bendera Merah Putih sebagai simbol seruan moral menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi Indonesia.SERANG | Bantenpopuler.com — Di tengah tekanan hidup yang kian berat—harga kebutuhan pokok yang terus menanjak, lapangan kerja yang makin sempit, serta rasa keadilan hukum yang kerap terasa jauh—wacana pengalihan pemilihan eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengemuka dan menuai sorotan publik. Rakyat kembali disebut dalam pidato dan slogan, namun pada inti kedaulatan—hak memilih pemimpin—posisinya justru terancam dipinggirkan.
Muncul gagasan agar pemilihan pemimpin eksekutif tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme DPR. Wacana tersebut dibungkus dengan alasan stabilitas dan efisiensi.

Seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan dan pemegang mandat tertinggi dalam sistem demokrasi.
Wacana ini mengemuka di tengah kondisi nasional yang sedang menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan sosial, serta berlangsung dalam ruang publik Indonesia.
Pemilihan langsung bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah pengakuan martabat rakyat yang lahir dari luka sejarah panjang dan mahal. Mengalihkannya ke ruang tertutup berisiko mengulang praktik masa silam—dengan bahasa yang lebih halus, namun niat yang sama: mengerdilkan hak publik dan mengurangi ruang koreksi rakyat terhadap kekuasaan.
Legitimasi kekuasaan berpotensi melemah. Dalam situasi krisis, negara membutuhkan mandat yang kuat—dan mandat itu hanya lahir dari kepercayaan rakyat, bukan dari lobi politik dan kalkulasi elit.
Sejarah dunia memberi pelajaran tegas. Di Venezuela, ketika pemilu kehilangan makna dan kepercayaan, ekonomi runtuh dan rakyat pergi. Di Mesir pasca Arab Spring, stabilitas yang dipaksakan membuat demokrasi menyempit—tenang di permukaan, rapuh di dasar. Di Myanmar, pembatalan suara rakyat menyeret negara ke konflik berkepanjangan. Di Sri Lanka, legitimasi yang menguap menumbangkan kekuasaan bukan oleh senjata, melainkan oleh kelelahan rakyat.
Tidak ada satu pun negara itu runtuh karena rakyat terlalu bebas. Mereka jatuh karena kekuasaan terlalu takut pada suara warganya sendiri.
Ini bukan ancaman gaduh, melainkan peringatan dingin: kekuasaan yang menjauh dari rakyat akan kehilangan pijakan. Rakyat mungkin bersabar, tetapi tidak lupa. Ketika suara yang sah terus dikecilkan, diam bukan tanda tunduk—melainkan jeda panjang sebelum rakyat menentukan arah baru bagi negeri ini.
Editor | Abah Elang Mangkubumi